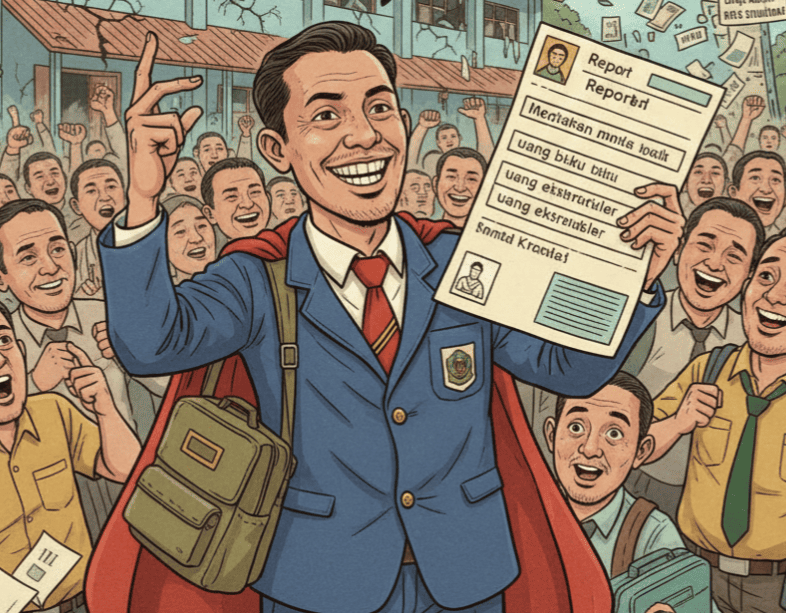MAGETAN (Lensamagetan.com) – Pagi ini di Magetan, udara masih cukup segar saat saya memacu kendaraan menuju salah satu SMA Negeri favorit. Agenda hari ini istimewa yakni, Gerakan Ayah Mengambil Rapor (Gemar). Sebuah inisiatif mulia berdasarkan Surat Edaran Bupati Magetan Nomor 100.3.5.2/499/403.108 Tahun 2025. Tujuannya keren, yakni memerangi fenomena fatherless dan memperkuat peran ayah dalam pendidikan anak.
Namun, siapa sangka, niat tulus untuk hadir demi masa depan anak justru berujung pada perenungan mendalam tentang jargon “Sekolah Gratis” yang selama ini didengungkan pemerintah.
Acara dibuka dengan khidmat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya menggema, membangkitkan rasa nasionalisme. Namun, suasana hangat itu perlahan berubah saat Kepala Sekolah memberikan sambutan. Satu kalimat yang terus terngiang di telinga saya adalah ketika beliau berucap: “Sejak saya kecil, sekolah itu tidak ada yang gratis, semua membayar.”
Kalimat itu jujur, namun menusuk. Di balik gedung sekolah negeri yang megah, pernyataan sang Kepala Sekolah seolah menelanjangi realitas bahwa sekolah gratis mungkin hanyalah “pepesan kosong” atau janji manis kampanye. Benar saja, firasat saya mengatakan bahwa setelah ini, “angka” akan berbicara.
Begitu Kepala Sekolah meninggalkan ruangan, estafet pembicaraan berpindah ke Ketua Komite. Di sinilah “menu utama” disajikan. Sebuah rekapitulasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dipaparkan dengan angka yang cukup fantastis Rp 1,3 Miliar lebih.
Dengan tameng dasar hukum bahwa “sumbangan” diperbolehkan, beban anggaran tersebut dibagikan kepada seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Karena waktu yang merambat siang dan mungkin rasa lelah, para orang tua akhirnya hanya bisa “manut” pada kesepakatan sumbangan Rp 100 ribu per bulan. Sebuah nominal yang bagi sebagian orang mungkin kecil, namun bagi yang lain adalah tambahan beban di tengah himpitan ekonomi.
Langkah kaki saya berlanjut menuju ruang kelas. Di sana, para siswa yang mungkin pengurus OSIS sudah menyambut. Bukan hanya dengan senyum, tapi juga catatan tunggakan uang kas kelas dan selembar kalender tahun 2026.
Menariknya, saat ditanya berapa harga kalender tersebut, mereka menjawab, “Harga kalendernya belum ditentukan, Pak.” Sebuah ketidakpastian kecil yang menambah daftar panjang tanda tanya di kepala para orang tua.
Puncak dari prosesi ini adalah saat berhadapan dengan wali kelas. Sebelum rapor diberikan, kami diminta mengisi surat pernyataan kesediaan menyumbang Rp 100 ribu per bulan, sesuai hasil rapat komite tadi.
Ada momen menarik saat pengisian surat. Sang wali kelas dengan halus menyarankan agar nominal sumbangan tidak di bawah angka tersebut. “Sama dengan ini boleh,” ujarnya sambil menunjukkan lembar orang tua lain yang sudah mengisi angka Rp 100 ribu. Di titik ini, kata “sumbangan” rasanya kehilangan makna sukarelanya dan lebih terasa seperti kewajiban yang dipatok.
Setelah tanda tangan dibubuhkan dan rapor berpindah tangan, saya melangkah meninggalkan gerbang sekolah. Gerakan Ayah Mengambil Rapor memang berhasil membawa saya ke sekolah, melihat lingkungan belajar anak, dan bersalaman dengan gurunya. Namun, di dalam saku, selain rapor, ada beban pikiran baru tentang rincian biaya yang harus dibayar, setiap bulanya Rp 100 ribu.
Sambil menghidupkan mesin motor, saya juga menatap kalender 2026 di tangan. Dalam hati membatin, “Berapa ya harga kalender ini nanti?” Rupanya, di sekolah “favorit” sekalipun, pendidikan memang investasi yang mahal. Dan benar kata Pak Kepala Sekolah, “di dunia ini, memang tidak ada sekolah yang benar-benar gratis”.(*)
Oleh : Wali Murid.